Validitas Kebenaran dalam Ilmu Kalam perspektif Filsafat Islam vs Ilmu Kalam
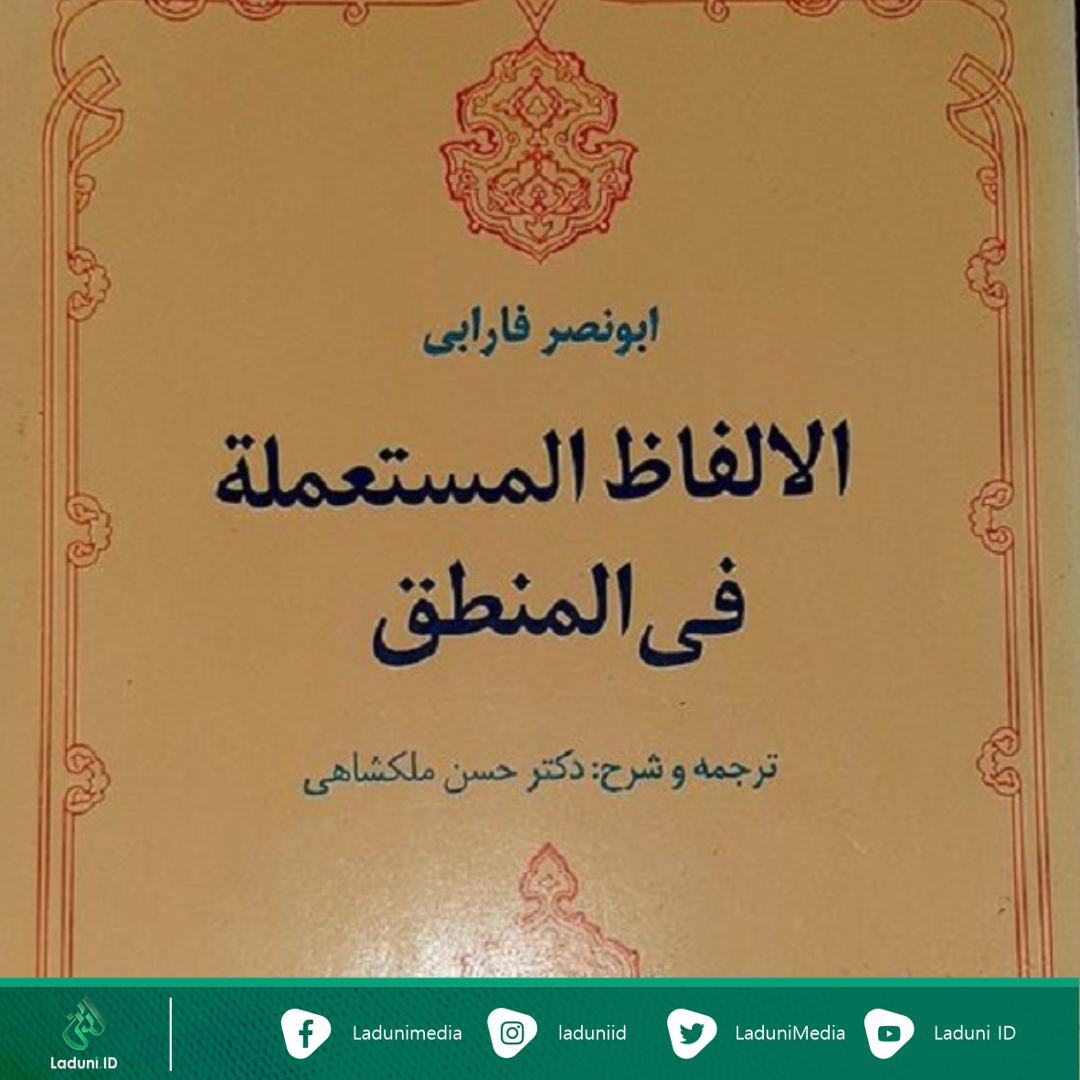
Laduni.ID, Jakarta – Ada perbedaan mendasar dan bersifat umum antara epistemologi dalam wacana filsafat dan wacana kalam adalah mengenai penggunaan istilah pengetahuan dharuri di kalangan para teolog. Term dharuri di kalangan filosof bertolak dari prinsip kausalitas tentang hubungan sebab-akibat, serta keterkaitan premis-konklusif dalam logika. Atas dasar ini, menurut al-Jabiri ada empat prinsip dalam kepastian logika dalam pandangan filosof yaitu prinsip kediaan (huwiyyah) yang memperlakukan fakta sebagaimana adanya dan hal yang fundamental yang terdapat padanya, prinsip tidak adanya kontradiksi, prinsip ketidakmungkinan menyimpulkan dari dua hal yang kontradiktif, dan prinsip kausalitas (M. Abid Al-Jabiri).
Secara umum, dalam kajian filsafat ilmu dikenal tiga teori klasik tentang kebenaran. Pertama, teori kebenaran korespondensi, maksudnya ialah kesesuaian atau kesepadanan antara pernyataan (ide) dengan kenyataan (realitas). Teori ini menekankan bahwa kebenaran ialah saling kesesuaian antara ide atau kepercayaan dengan realitas atau fakta, yakni dengan membandingkan atau menyamakan dengan realitas. Teori ini bersifat empiris, karena suatu ide dianggap benar jika ia cocok dengan realitas, bukan realitas yang harus sesuai dengan ide. Teori ini juga telah lama diperkenalkan oleh Ibnu Sina, menurutnya, suatu perkataan dianggap benar jika perkataan dan keyakinan itu sesuai dengan kenyataannya.
- Baca juga: Jelaskan Perbedaan Ilmu Akidah dan Ilmu Kalam, Kiai Abdul Wahab Ahmad: Ada Perbedaan Mendasar
Kedua, teori kebenaran koherensi. Pengetahuan yang memiliki kebenaran koherensi adalah pengetahuan yang diperoleh dengan mengikuti hukum-hukum logika, karenanya tidak terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi. Pengetahuan ini tidak terdapat pertentangan dalam dirinya (contradiction in terminis), juga tidak bertentangan dengan pengetahuan terdahulu. Pengetahuan ini menekankan pada ketepatan berpikir.
Ketiga adalah teori kebenaran pragmatisme (Louis O. Kattsoff). Teori ini dikembangkan dan dianut oleh filsuf-filsuf pragmatisme dari Amerika, seperti Charles S. Peirce dan William James. Bagi mereka, kebenaran sama artinya dengan kegunaan. Jadi, ide, konsep, pernyataan, atau hipotesis yang benar adalah ide yang berguna. Ide yang benar adalah ide yang paling mampu memungkinkan seseorang berdasarkan ide itu melakukan sesuatu secara paling berhasil atau tepat guna. Dengan kata lain pengetahuan dianggap benar jika bernilai praktis.
Dari tiga macam teori klasik tentang kebenaran di atas, Ilmu Kalam sering menggunakan teori kebenaran koherensi. Sebagian besar ulama ahli kalam berpendapat bahwa akidah dan hukum akal harus meyakinkan dan bersifat qath’i. Bagi kalangan rasionalis, dalam hukum akal tidak boleh ada perbedaan pendapat, nafi dan itsbat, dengan kontradiksinya sekiranya dipertentangkan dengan yang lainnya melalui dalil yang berbeda pada saat ditetapkan. Jika tidak dilakukan demikian maka akan terjadi keseimbangan antara kebenaran dan kesalahan, yang benar dan yang salah sama. Sementara masalah yang diperselisihkan tidak mungkin mengandung kebenaran dan kesalahan secara bersamaan. Seperti ucapan seseorang, “Ahmad ada di dalam rumah pada jam tujuh pagi.” Kemudian ada orang lagi yang berkata, “Ahmad tidak ada di dalam rumah pada jam tujuh pagi.” Kedua pernyataan tersebut tidak mungkin benar semua. Kebenaran koherensi ini mengharuskan adanya konsistensi berpikir logik. Teori koherensi ini menjadi alur yang cukup kuat dalam sistem berpikir kaum Mu’tazilah. Seperti ‘Abd al-Jabar dengan penekanannya pada konsistensi antara premis mayor (mujmal), premis minor (mufashshal), dan konklusi (ta’amul). Ia memiliki sistem berpikir logika yang sangat ketat.
- Baca juga: Syarah Penamaan Aqidah dan Kalam
Contohnya:
(a) Berbuat dzalim adalah jahat (premis mayor);
(b) Perbuatan ini adalah dzalim (premis minor);
(c) Jadi perbuatan ini adalah jahat (konklusi)
Menurut teori ini kebenaran suatu proposisi hanya dapat diterima jika sesuai dengan proposisi sebelumnya yang sudah diterima kebenarannya. Sebagai contoh, problematika kebebasan kehendak menurut aliran Mu’tazilah berkaitan erat dengan prinsip keadilan Tuhan yang mereka kembangkan. Mereka memandang bahwa keadilan Tuhan menjadi hilang jika seseorang dituntut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak ia kerjakan, atau ia dihisab tentang perbuatan yang tidak ia kehendaki. Keadilan Allah menuntut bahwa manusia harus bebas berkehendak. Karena tanpa adanya kebebasan ini, kenabian dan risalahnya tidak ada artinya, tidak ada dasar bagi syari’ah atau taklif bahkan untuk apa pengutusan para Rasul kepada orang yang tidak mempunyai kebebasan dalam mengikuti dan mendengarkan dakwah mereka.
Masalahnya berbeda ketika kalangan Asy’ariyah yang menekankan kekuasaan mutlak Tuhan, di mana ruang untuk koherensi menjadi “tertutup” karena adanya keserbabolehan (sultah al-tajwiz). Kaitannya dengan hal ini, al-Asy’ari menulis dalam al-Ibanah-sebagaimana dikutip Harun Nasution, bahwa Tuhan tidak tunduk kepada siapapun, di atas Tuhan tiada suatu Zat yang lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang tidak boleh diperbuat oleh Tuhan. Al-Ghazali, salah seorang teolog kenamaan Asy’ariyah menyatakan bahwa Tuhan dapat berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, dapat memberikan hukum menurut kehendak-Nya, dapat menyiksa orang yang berbuat baik jika itu yang dikendaki-Nya, dan dapat memberi upah kepada orang kafir jika itu yang dikehendaki-Nya juga (Harun Nasution). Ini semua berdasar dari kekuasaan mutlak Tuhan.
Pada faktanya Semua aliran dalam pemikiran kalam berpegang kepada wahyu sebagai sumber pokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya memahami wahyu sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami wahyu sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran dengan merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Untuk kasus pertama sering diistilahkan dengan muhkam sedang yang kedua dinamakan dengan mutasyabih. Contoh untuk yang muhkam adalah ayat-ayat tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji dan ancaman. Sementara untuk yang mutasyabih contohnya adalah ayat-ayat tentang Asma’ Allah dan sifat-sifatnya.
Kenyataan adanya ayat muhkam dan mutasyabih ini memberikan pengertian bahwa meski al-Qur’an sebagai sumber utama, tetapi ia tidak selalu dapat memberikan ketentuan hukum pasti.
Secara hirarkis, al-Qur’an merupakan sumber rujukan utama dari semua argumentasi dan dalil. Al-Qur’an adalah dalil yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan dalil yang membuktikan benar dan tidaknya suatu ajaran. Sumber lainnya yang diakui adalah nalar, terlepas seberapa besar nalar digunakan tetapi memang telah terjadi, khususnya dalam kajian kalam, dialektika antara teks dengan nalar. Menurut Qadhi Abd. al-Jabbar, akal merupakan potensi manusia untuk memperoleh pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang kewajiban moralitas, hanya saja Abd. Al-Jabbar tidak sampai pada konsep akal sebagai potensi nalar-spekulatif, karena keterkaitan kuatnya dengan teks-teks keagamaan.
Kaitannya dengan akal, al-Asy’ari menolak sebagian besar pendapat Mu’tazilah dengan mengatakan bahwa segala sesuatu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Bahkan menurut Harun Nasution, pada aliran ini tidak jelas apakah akal dapat mengetahui yang baik dan jahat. Memang akal dapat mengetahui Tuhan tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui dan berterima kasih kepadanya. Juga akal tak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia.
Memang, secara keseluruhan bangunan pemikiran Asy’ariyah sebetulnya mencoba menciptakan suatu posisi yang moderat hampir dalam semua isu teologis yang menjadi perdebatan pada zamannya. Asy’ariyah membuat penalaran tunduk kepada otoritas wahyu dan secara otomatis menolak kehendak bebas manusia yang dilakukan secara sukarela, yang menghilangkan kehendak bebas manusia yang kreatif dan menekankan kekuasaan tuhan dalam semua yang terjadi di belakang ayat-ayat al-Qur’an.
Sebagaimana Seyyed Hossein Nasr menyatakan bahwa Asy’ariyah memasukkan semua penyebab horisontal ke dalam penyebab vertikal, yakni kehendak Tuhan, dengan cara menyederhanakan alam semesta menjadi sejumlah atom yang bergerak dalam ruang dan waktu yang diskontinu, sehingga tak ada sesuatupun yang memiliki sifat-sifat khusus. Tidak heran jika kemudian Asy’ariyah menjadi bertentangan dengan filsafat Islam (Seyyed Hossein Nasr).
Note: Kitab Mantiq karya Al Farabi
Penulis: Firmansyah Djibran El'Syirazi B.Ed, Lc
Editor: Daniel Simatupang
Kunjungi Juga
- Pasarkan Produk Anda dengan Membuka Toko di Marketplace Laduni.ID
- Profil Pesantren Terlengkap
- Cari Info Sekolah Islam?
- Mau Berdonasi ke Lembaga Non Formal?
- Siap Berangkat Ziarah? Simak Kumpulan Info Lokasi Ziarah ini
- Mencari Profil Ulama Panutan Anda?
- Kumpulan Tuntunan Ibadah Terlengkap
- Simak Artikel Keagamaan dan Artikel Umum Lainnya
- Ingin Mempelajari Nahdlatul Ulama? Silakan
- Pahami Islam Nusantara
- Kisah-kisah Hikmah Terbaik
- Lebih Bersemangat dengan Membaca Artikel Motivasi
- Simak Konsultasi Psikologi dan Keluarga
- Simak Kabar Santri Goes to Papua















Memuat Komentar ...